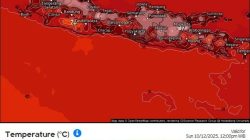BERITAKOTAONLINE.ID – Nama Ki Hajar Dewantara harum di seluruh pelosok negeri sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan gagasannya yang tak lekang waktu.
Namun, sedikit yang tahu: tokoh yang begitu diagungkan ini ternyata hanya lulus setara Sekolah Dasar dan bahkan pernah drop out dari bangku kuliah.
Lalu, bagaimana bisa sosok dengan latar belakang pendidikan yang menurut ukuran sekarang terbatas, justru menjadi pelita pendidikan bagi generasi bangsa?
Lahir di Tengah Kemewahan, Tumbuh dalam Keterbatasan
Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Soewardi Soeryaningrat pada 2 Mei 1889, di lingkungan bangsawan Yogyakarta.
Keluarganya masih berkerabat dengan Paku Alam, tetapi garis takdir berkata lain.
Kekayaan keluarganya perlahan menyusut.
Dari status bangsawan, keluarganya turun menjadi bagian dari “aristokrasi yang tak punya hak istimewa”, sebagaimana diungkap sejarawan Savitri Prastiti Scherer.
Kondisi ini sangat memengaruhi akses pendidikan Soewardi.
Alih-alih bersekolah di Hoogere Burgerschool (HBS) atau dikirim ke Belanda seperti anak bangsawan lainnya, ia hanya bisa masuk ke Europese Lagere School (ELS) sekolah rendah yang secara status setara SD zaman sekarang.
Namun, bukan berarti ELS sekolah sembarangan. Ini adalah sekolah elite, dan hanya segelintir anak pribumi yang bisa masuk, itupun dengan syarat yang ketat.
“Penerimaan anak pribumi dibolehkan asal jumlahnya kurang dari jumlah anak Belanda,” tulis peneliti sejarah, Fakhriansyah.
Soewardi muda harus berjuang keras di lingkungan pendidikan yang bukan hanya asing, tetapi juga penuh diskriminasi. Tahun 1896, ia resmi terdaftar di ELS.
Setelah lulus, dia mencoba peruntungan di STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen), sekolah kedokteran untuk bumiputera.
Tapi harapannya kandas fisik yang lemah dan sering sakit membuatnya terpaksa mundur sebelum lulus. Drop out.
“Beasiswanya dicabut karena terlalu sering tak masuk sekolah,” catat sejarawan Djoko Marihandono.
Dari Drop Out ke Jalan Perjuangan
Setelah tak lagi bersekolah, Soewardi tak larut dalam keterpurukan. Ia banting tulang menjadi buruh pabrik gula, petugas perkebunan, hingga akhirnya menemukan panggilannya sebagai wartawan.
Di sinilah benih pemikiran besarnya mulai tumbuh. Dunia pendidikan baginya bukan soal gelar, tapi soal pembebasan.
Puncak pengabdiannya tercatat saat mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada 1922.
Sebuah sekolah yang lahir sebagai perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif.
Di sekolah ini, siapa pun bisa belajar—tanpa memandang kasta atau latar belakang.
Sejarawan Jepang, Tsuchiya Kenji, menyebut Taman Siswa sebagai bentuk nyata demokratisasi pendidikan. Tak ada sekat antara bangsawan dan rakyat jelata. Semua sama, semua diajak berpikir kritis dan mandiri.
Dalam proses mendidik, Ki Hajar merumuskan filosofi yang kini melekat dalam dunia pendidikan nasional:
Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan memberi teladan),
Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun semangat),
Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan).
Warisan Tanpa Tanda Lulus
Bagi Ki Hajar Dewantara, mendidik bukan perkara ijazah, tetapi tentang keberanian untuk berpikir dan memanusiakan manusia.
Meski tak bergelar sarjana, gagasan dan semangatnya telah melampaui batas akademik mana pun.
Ia membuktikan, pendidikan sejati bukan sekadar menempuh bangku formal—melainkan bagaimana menciptakan ruang tumbuh bagi jiwa-jiwa yang ingin merdeka.
Soewardi Soeryaningrat wafat pada 26 April 1959. Tak lama berselang, negara mengukuhkannya sebagai pahlawan nasional.
Lalu, melalui Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959, tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Kini, setiap 2 Mei, negeri ini bukan hanya mengenang seorang guru bangsa tetapi juga merayakan keberanian seseorang yang, meski tak berijazah tinggi, justru menjadi suluh bagi masa depan pendidikan Indonesia (*).
Editor: Enrizal Mustafa
=========================